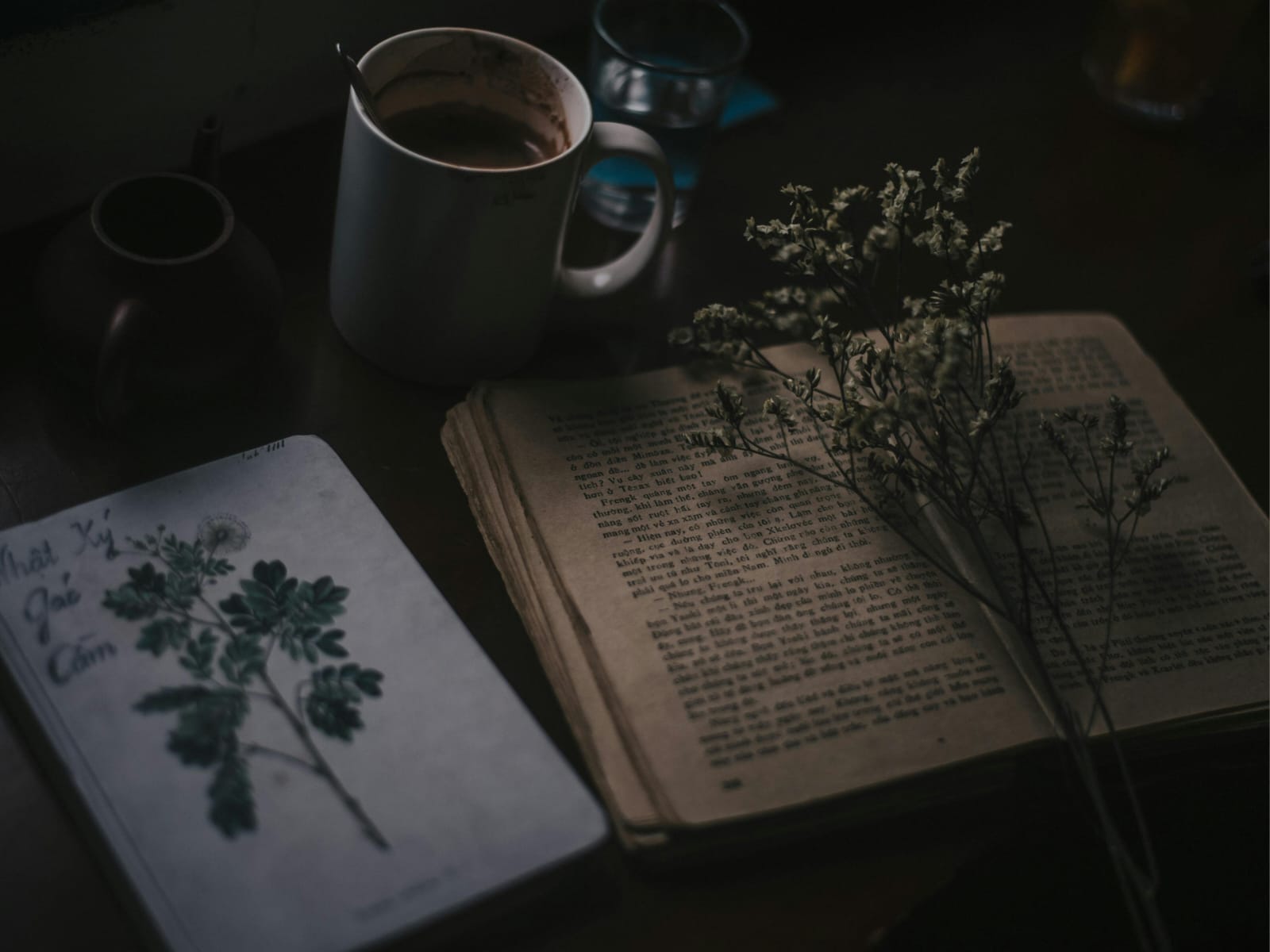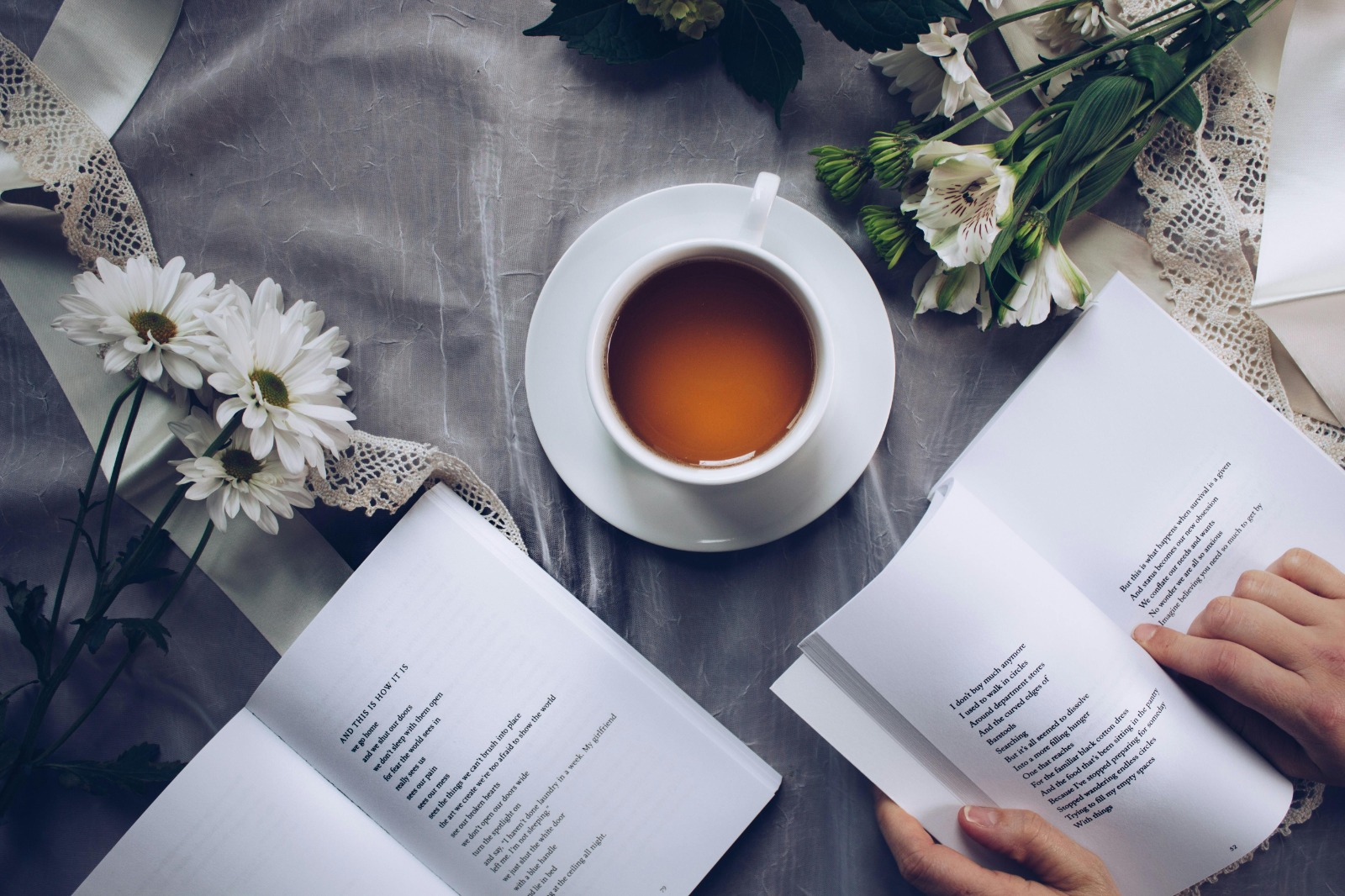Membaca yang Seharusnya Tidak Layak Dibaca: Sebuah Catatan Tentang Puisi
“Tulisan ini sebagai cacatan ketika saya diundang menjadi juri lomba baca puisi dalam rangka peringatan Bulan Bahasa Nasional yang diselenggarakan oleh HMP PBSI FKIP UPI Sumenep pada Rabu 29 Oktober kemarin”
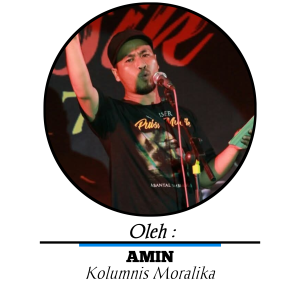
Sebagai juri, saya berhak terkejut. Ketika saya mendapat laporan bahwa sekitar 150 peserta yang ikut lomba dengan lima pilihan teks puisi yang super panjang. Dunia Bogambola karya Sosiawan Leak, Aku Harus Bagaimana karya Gus Mus, Sajak Kepada Kawan karya Chairil Anwar, Balada Orang-orang Tercinta karya Rendra dan Sajak Murid Bolos karya Nanoq da Kansas.
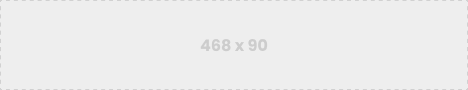
Bisa dibayangkan dengan pilihan teks puisi di atas ditambah banyaknya peserta, bagaimana nasib saya sebagai juri?
Membaca puisi di atas panggung adalah seni tersendiri. Ia bukan sekadar melafalkan larik-larik indah, melainkan upaya menghidupkan makna, membentuk suasana, dan menghadirkan emosi di hadapan pendengar. Namun, di balik gemuruh suara dan gestur di panggung, ada hal yang sering terabaikan: tidak semua puisi cocok untuk dibacakan di ruang publik, apalagi dalam sebuah ajang lomba.
Dalam banyak perlombaan baca puisi, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, pilihan teks kerap menjadi masalah yang tak pernah benar-benar dibahas. Panitia seringkali asal “ambil” puisi karya penyair terkenal, tanpa menimbang apakah teks itu memang ditulis untuk dibacakan atau tidak. Padahal, keputusan ini sangat menentukan keberhasilan sebuah acara dan keadilan bagi para peserta.
Penyair Leon Agusta, dalam bukunya HUKLA, pernah memperkenalkan istilah menarik: puisi kamar dan puisi auditorium. Dua istilah ini sederhana, tetapi membuka cara pandang baru tentang fungsi dan kehidupan sebuah puisi.
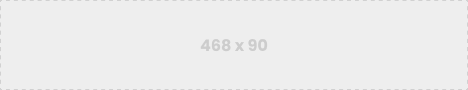
Puisi kamar lahir dari keheningan; ia intim, reflektif, dan cenderung kontemplatif. Puisi seperti ini lebih cocok dibaca dalam ruang pribadi, dinikmati perlahan-lahan di antara jeda waktu dan kesunyian.
Sebaliknya, puisi auditorium hidup dari suara. Ia memerlukan ruang, penonton, dan tubuh pembaca untuk menghidupkan maknanya. Diksi dan ritmenya tegas, emosinya mengalir keluar, bukan ke dalam.
Klasifikasi ini, paling tidak bisa menjadi pertimbangan utama dalam memilih teks lomba. Ketika panitia mengabaikan hal itu, peserta bisa terjebak dalam situasi yang tidak adil: mereka diminta menampilkan sesuatu yang teksnya memang tidak dirancang untuk tampil. Alhasil, pembacaan kehilangan energi dan puisi pun kehilangan ruhnya.
Fenomena ini kerap terlihat di berbagai lomba baca puisi. Ada peserta yang begitu berusaha memaksakan ekspresi pada teks yang sebenarnya sunyi.
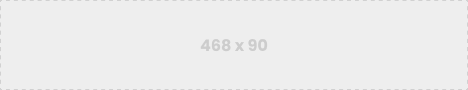
Gestur menjadi berlebihan, intonasi terdengar palsu dan makna puisi justru kabur. Hal ini bukan semata kesalahan peserta, tetapi juga akibat dari pemilihan teks yang tidak tepat.
Banyak panitia memilih puisi karena popularitas penyairnya, bukan karena kekuatan performatif teksnya. Ada pula yang menganggap semakin “berat” puisinya, semakin tinggi nilai seninya. Padahal, berat secara isi tidak selalu berarti kuat ketika dibacakan.
Selain persoalan isi, durasi dan efisiensi waktu juga tak kalah penting. Puisi yang terlalu panjang bisa menguras fokus juri dan penonton, sementara puisi yang terlalu pendek sering kali gagal membangun suasana yang utuh. Panitia yang bijak seharusnya menimbang hal ini sejak awal, bukan hanya untuk kelancaran lomba, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan artistik acara.
Sebuah lomba baca puisi yang baik lahir dari panitia yang memahami hakikat apresiasi sastra. Tugas mereka bukan hanya menyiapkan tempat dan daftar peserta, tetapi juga memastikan teks yang dipilih dapat hidup di atas panggung. Idealnya, pemilihan puisi dilakukan melalui kurasi yang melibatkan penyair, pengajar sastra, atau pelaku teater—mereka yang memahami baik struktur teks maupun potensi performatifnya.
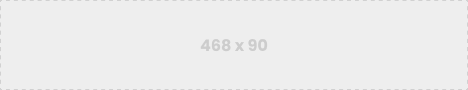
Membaca puisi di ruang publik adalah tindakan estetis sekaligus etis. Etis, karena ia memerlukan penghormatan terhadap karya orang lain; estetis, karena ia menuntut kepekaan dalam menafsirkan dan menampilkan keindahan.
Pemilihan teks yang tepat menjadi bagian dari etika itu. Panitia yang memilih puisi tanpa mempertimbangkan konteks pembacaan berarti abai terhadap ruh kesenian itu sendiri. Sebab, membaca puisi bukan hanya soal tampil di panggung, melainkan soal menghidupkan kata-kata agar bisa berjumpa dengan pendengarnya secara jujur.
Dalam konteks ini, efisiensi waktu dan bentuk lomba juga bukan sekadar urusan teknis. Ia bagian dari cara menghargai puisi agar tidak kehilangan makna di tengah tuntutan format.
Pada akhirnya, lomba baca puisi bukanlah sekadar kompetisi, melainkan perayaan sastra. Terkandung upaya untuk mendekatkan masyarakat pada puisi. Membuka ruang dialog antara penyair, pembaca, dan pendengar. Namun, perayaan itu hanya akan bermakna jika dilandasi oleh pemahaman yang benar terhadap hakikat puisi itu sendiri.
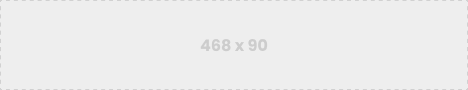
Sebab sesungguhnya, membaca puisi bukan tentang siapa yang paling lantang atau paling ekspresif, tetapi siapa yang paling peka dalam menangkap napas dan irama di balik kata-kata. Keindahan sejati pada puisi, sejatinya mampu menemukan ruangnya—di antara kejujuran pembaca, kecerdasan panitia, dan keheningan yang lahir dari pemahaman. (*)
Join WhatsApp channel moralika.com agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.
Gabung